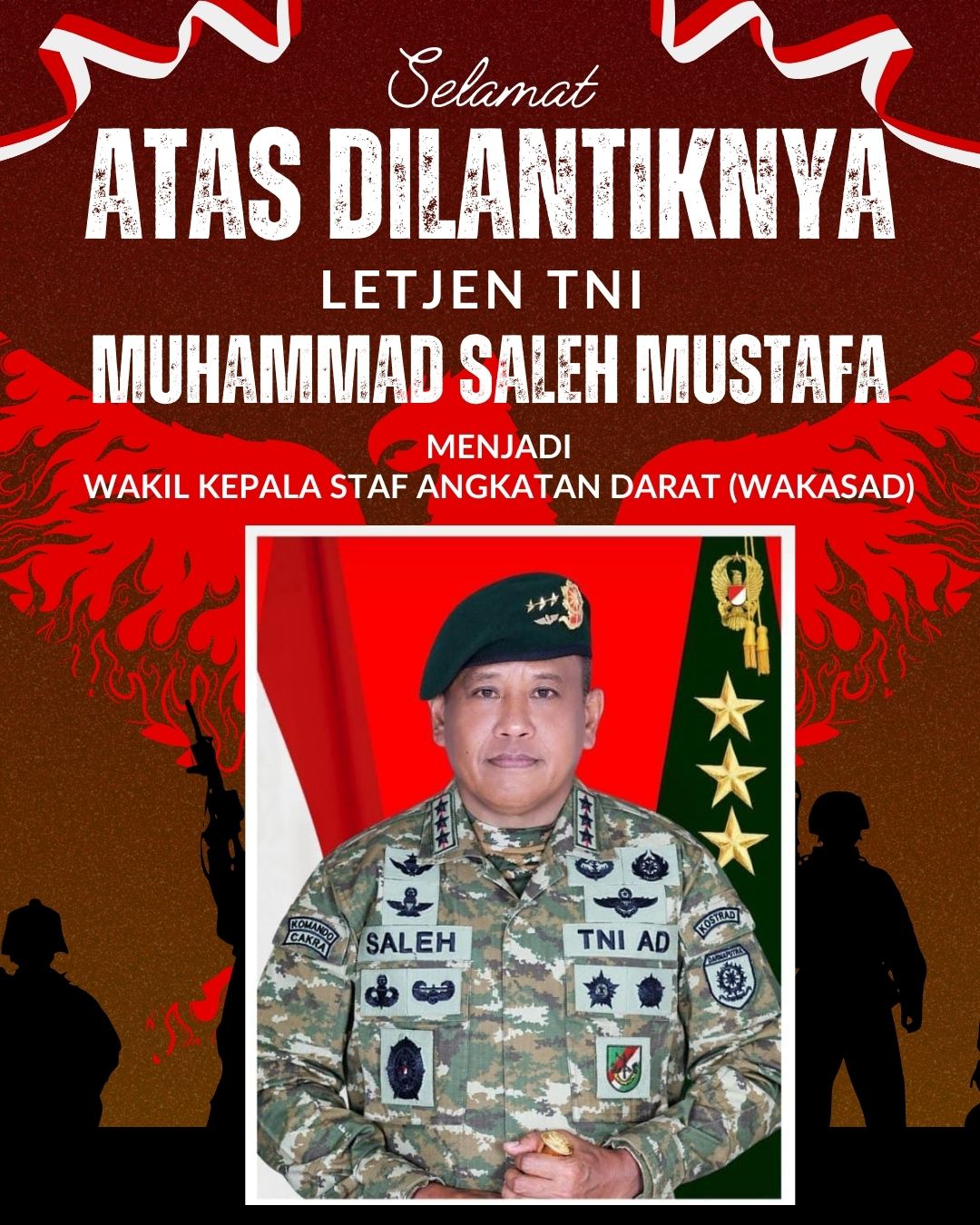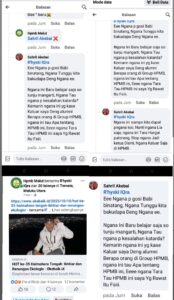Wilson Colling. Praktisi Hukum
————————————
FAKTA HUKUM.ID – JAKARTA,
Penegakan hukum di Indonesia seringkali terasa berjarak dengan denyut nadi keadilan masyarakat. Aparat hukum, mulai dari polisi hingga hakim, kerap terjebak dalam pendekatan dogmatis yang kaku, seolah hukum adalah entitas steril yang bisa diterapkan secara seragam di seluruh nusantara. Padahal, Indonesia adalah mozaik budaya yang kaya. Menempatkan seorang polisi dari Jawa di Sumatera Selatan, atau dari Sumatera di Papua, tanpa membekalinya dengan pemahaman sosiologis dan budaya setempat, sama saja dengan mengirimnya ke medan tanpa peta.
Tantangan kultural ini bukan sekadar persoalan adaptasi personal, melainkan fondasi utama bagi tegaknya hukum yang berkeadilan. Bagaimana mungkin seorang aparat dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat jika ia tidak memahami “bahasa” sosial mereka? Langkah pertama dan paling krusial bagi setiap aparat yang bertugas di wilayah baru adalah menanggalkan sementara atribut kekuasaan dan mendekati masyarakat dengan kerendahan hati. Mereka harus menyelami nilai-nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang hidup—memahami apa yang dianggap patut dan apa yang tabu dalam komunitas tersebut.
Setelah denyut sosial itu dirasakan, barulah “seragam” hukum dan keadilan dapat dikenakan kembali. Dengan begitu, hukum tidak lagi tampil sebagai alat yang dingin dan asing, melainkan sebagai instrumen yang relevan dan menjawab kebutuhan nyata. Hal ini tidak hanya berlaku bagi polisi di lapangan, tetapi juga bagi para hakim di ruang sidang. Putusan yang adil seringkali lahir dari pemahaman mendalam terhadap konteks sosial perkara, bukan sekadar penerapan pasal-pasal secara mekanis.
Transformasi Pendidikan Hukum Mendesak
Sayangnya, akar persoalan ini juga tertanam dalam sistem pendidikan hukum kita. Para pengelola program studi hukum masih banyak yang terbelenggu dalam paradigma usang, seolah mengajarkan hukum pidana dan hukum acara secara dogmatis adalah satu-satunya cara menjaga marwah keilmuan. Anggapan ini adalah sebuah kekeliruan besar.
Tren ilmu pengetahuan global saat ini justru bergerak ke arah pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Ilmu hukum tidak bisa lagi berdiri angkuh di menara gadingnya. Ia harus berdialog dengan sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya untuk dapat memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (law in action), bukan hanya hukum dalam kitab undang-undang (law in the books).
Mempelajari hukum tidak boleh berhenti pada doktrin dan pasal. Mahasiswa hukum, calon polisi, jaksa, dan hakim perlu diajarkan bagaimana masyarakat merespons hukum. Lebih penting lagi, mereka harus paham bahwa ketika hukum negara dirasa tidak adil atau tidak hadir, masyarakat memiliki kapasitas untuk menciptakan “hukum”-nya sendiri. Fenomena inilah yang sering menjadi sumber gesekan antara aparat dan warga.
Mengembalikan Polisi pada Khitahnya
Sudah saatnya kita secara serius mengembalikan institusi kepolisian pada tugas konstitusionalnya yang luhur: memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Mandat ini mustahil terwujud secara optimal tanpa pemahaman sosiologis yang mendalam.
Di samping pembenahan paradigma keilmuan, membangun budaya jujur adalah pilar yang tidak bisa ditawar, baik pada level kelembagaan maupun individual di tubuh Polri. Integritas adalah mata uang utama kepercayaan publik. Ketika aparat penegak hukumnya berintegritas dan mampu membaca realitas sosial dengan baik, maka budaya hukum yang tumbuh akan mampu mendekatkan substansi keadilan hukum dengan rasa keadilan rakyat. Inilah esensi dari negara hukum yang membumi dan berpihak pada warganya.
Bung NUEL
Jurnalis Fakta Hukum.id